
Sufi Agung, Pujangga Jawa terakhir, R. Ng Ronggowarsito dengan segala kebijaksanaan yang menyelimutinya telah berkata;
“Jaka lodhang gumandhul,
Praptaning pang ngethengkrang sru muwus,”
Jaka Lodhang bergantungan di pohon,
Di dahan, kemudian duduk santai sambil berkata keras (kurang sopan).
Sang Pujangga mengawali narasinya dengan menggambarkan sosok Jaka Lodhang yang bergelantungan di pohon, tepatnya di dahan. Kata ‘gumandhul’ berakar dari kata ‘gandhul’ yang diseseli (disisipi) dengan huruf ‘um’ setelah huruf pertama, menjadi ‘gumandhul’. Dalam linguistik Jawa, rangkaian dari kata gandhul kerap digunakan untuk menggambarkan suasana yang terbilang sakral. Misalkan beberapa kata berikut,
- ‘Kramat gandhul’ yang secara etimologi berarti tuah yang bergantungan. Kata ini biasanya disematkan kepada seseorang yang memiliki nasab luhur, keturunan orang-orang hebat, tedaking kusuma rembesing madu tedhaking andanawarih.[1] Misalkan putra seorang kiai yang lazim dipanggil gus, atau putra bangsawan yang lazim disebut Raden, yang mendapatkan penghormatan, kemulian, atau kekeramatan disebabkan oleh jasa dari orang tua dan leluhurnya. Tanpa perlu bersusah payah untuk menggapainya. Hal yang demikian orang Jawa kerap menamainya dengan Kramat gandhul.
- ‘Makna Gandhul’ yang arti harfiahnya makna yang bergantung. Kata ini sering digunakan dalam khazanah pesantren-pesantren di Indonesia, khususnya Jawa. Sebutan untuk terjemahan teks Arab dalam bahasa Jawa dengan huruf pegon. Terjemahan tersebut ditulis secara agak miring sehingga mempunyai kesan menggantung.
- ‘Ghumandhul tanpo centelan’ artinya bergelantungan tanpa sebuah sandaran. Kalimat ini sering keluar dalam sastra lisan (foklore) Jawa. Biasanya dapat ditemui dalam tradisi ‘Ujub wilujengan’ (preambule) kenduri atau selamatan. Kalimat tersebut melambangkan maqom Ahadiyah, ketunggalan Tuhan Yang Maha Esa.
- ‘Dharma Gandhul’ nama sebuah karya sastra yang menceritakan runtuhnya Majapahit disusul beridirinya Kerajaan Islam Demak, juga berisi beberapa jangka (ramalan) dan wejangan tentang sebuah wewadi (rahasia).[2]
Dalam narasinya tersebut, Sang Pujangga menggambarkan sosok Jaka Lodhang yang tak lain adalah dirinya sendiri sedang bergelantungan. Sebuah metafor tentang pencapaian spiritual (maqam) tertentu. Sang Pujangga tak ubahnya sosok Resi Subali yang bertapa (meditasi) Ngalong di Gunung Sunyapringga (kesunyian di tengah keruwetan) dengan cara bergelantungan di dahan pohon dengan posisi kepala berada dibawah (Asana Sirsasana)[3] bak seekor kelelawar. Dengan cara itu, Resi Subali mendapat anugerah Dewata berupa Aji Pancasona (lima kesunyian) yang jika ia mati dan menyentuh bumi, seketika akan hidup kembali.[4]
Jaka Lodhang bergelantungan sambil memegang dahan pohon. Dalam kosmologi Jawa, pohon (kayu) adalah artikulasi kehidupan. Kayu terambil dari serapan kata dalam Bahasa Arab, Hayyu yang artinya hidup, salah satu dari nama Tuhan yang terbaik (Asma Al-Husna), Al-Hayyu. Karenanya, setiap membuka pagelaran wayang kulit, Sang Dalang sebagai simbolisme (sanepa) Tuhan, selalu memunculkan gunungan (kayon) yang melambangkan terjadinya kehidupan itu sendiri.[5] Sebaliknya lakon yang akan diceritakan adalah komponen terkecil dari sebuah jantra kehidupan.
Jaka Lodhang bergelantungan di dahan (pang), cabang dari pohon kehidupan yang lebih besar. Secara lebih mendalam, R. Rg. Sastrasadarga telah menjelaskan makna tersembunyi dari sebuah dahan, Pang punika kajeng ingkang cawang-cawang, ateges pecahing karep (dahan yang dimaksud adalah keinginan yang bermacam-macam, maksud yang dikehendaki adalah timbulnya sebuah keinginan).[6]
Selanjutnya Jaka Lodhang berbicara dengan nada keras, ceplas-ceplos, meninggalkan pelbagai etika kesopanan (murang tata) yang dijunjung tinggi oleh kebanyakan orang Jawa, terutama kalangan Ningrat. Disini R. Ng. Ranggawarsito menggunakan nada-nada satire, sedangkan ia sendiri adalah orang yang hidup ditengah-tengah lingkungan Keraton Surakarta yang sarat dengan nilai sopan santun (unggah-ungguh), kesusilaan (trapsila), dan etika (subasita). Dengan nada satire tersebut, Sang Pujangga hendak melakukan otokritik terhadap hegemoni, otoritarian dan feodalisme Mataram Islam. Trah Panembahan Senopati, yang dalam hal ini diwakili oleh Kraton Kasunanan. Juga kondisi sosial yang terjadi pada waktu itu. Senada dengan kata yang dilontarkan oleh Sujiwo Tejo, Bila dengan ‘jancuk’ pun tak sanggup aku menjumpaimu, dengan air mata mana lagi dapat ku ketuk pintu hatimu.
Dalam tradisi Jawa, R. Ng. Ronggowarsito bukan sosok yang pertama dalam menggunakan diksi-diksi satire sebagai media otokritik terhadap penguasa berikut neven-neven dan tradisi yang melingkupinya. Terdapat sederetan nama yang menghiasi khazanah intelektual Jawa, sebut saja nama Ki Ageng Kutu Suryangalam, Ki Ageng Pengging, Syaikh Siti Jenar, Pangeran Panggung, Man Doblang, Samin Surosentiko, atau Cak Durasim.
Dus, jauh dikedalaman sanubari R. Ng. Ronggowarsito, tertanam kuat rasa cinta dan kebanggaan terhadap Keraton Kasunanan Surakarta meskipun disisi lain ia melancarkan otokritik. Mustahil tokoh sekaliber R. Ng. Ronggowarsito yang dibesarkan dalam lingkup keraton melakukan tindakan makar. Apalagi ia pernah meneguk manisnya pengetahuan dari Sinuhun Pakubuwono IV dan Panembahan Buminoto, raja dan pembesar Keraton Kasunanan Surakarta. Well, tidak mesti sebuah otokritik identik dengan perlawanan, apalagi sebuah pembangkangan. Tidak. Jika meminjam istilah dari Gus Dur, Ketundukan di dalam (inner obedience) yang tampak sebagai pengingkaran di luar (outer disobedience).[7] Lebih lanjut Presiden ke-4 RI itu menjelaskan, Berapa orangkah dari kalangan kita yang sanggup mengikuti perintah dalam penghayatan di dalam seperti itu? Mampukah kita untuk melepaskan diri dari ketundukan luar untuk mengejar ketundukan di dalam, suatu hal yang lebih bersifat pengembangan dan mempunyai nilainya sendiri yang mendasar? Bukankah kebalikannya yang lebih banyak kita lakukan, yaitu ketundukan di luar dan melawan di dalam? Tanyakan kepada para alumni penataran P4, kalau tidak percaya![8]
Pada level-level tertentu, seseorang dengan sengaja menutupi jatidirinya demi menggapai hal-hal yang lebih tinggi. Karena itu, terdapat ungkapan yang sempat populer di Inggris, Do not judge a book by its cover, the soul is more profound than the skin.[9] Dalam bahasa yang sederhana namun sarat dengan nilai sufistik, Gus Miek (KH. Hamim Djazuli) pernah berkata, Dadio sak élék-éléke manungsa menungso tapi luhur mungguhing Gusti Allah (Jadilah seburuk-buruk manusia di mata manusia tetapi luhur di mata Allah.[10]
Karena itu, menyandarkan penilaian pada aspek lahiriyah semata akan berakibat menjungkir balikkan sudut pandang dan perspektif kita, sehingga pada gilirannya akan melahirkan pemahaman yang parsial, tidak objektif, dan jauh dari nilai-nilai kebenaran. Demikian.
[1] Sebuah ungkapan di Jawa untuk menggambarkan keturunan para Kusuma bangsa, orang-orang hebat terdahulu, dan kaum bangsawan.
[2] Lebih lengkapnya baca Darmagandhul: Carita adege nagara Islam ing Demak bedhahe Majapahit kang salugune wiwite wong Jawa ninggal agama Buddha banjur salin agama Islam, karangan KRT. Tandhanagara dditerbitkan oleh TB. Sadu-Budi Solo tahun 1959. Atau baca teks yang telah diterjemah dan diuraikan oleh Damar Shashangka.
[3] Pujiastuti Sindhu, Hidup sehat dan seimbang dengan Yoga,(Bandung, Qanita, 2007) hlm 146-147.
[4] Untuk teks lengkap aji berikut cara mengamalkannya baca; Sang Indrajati, Kitab Wedha Mantra, (Solo, Sadu Budi, 1979) hlm 48-49.
[5] Untuk keterangan lebih komperehensif baca; Tuti Sumukti, Semar: Dunia Batin Orang Jawa, (Yogyakarta, Galang Press, 2006), hlm 67-69.
[6] R. Rg. Sastrasudarga, Jangka Ronggo Warsito, (Solo, Sadu Budi, tt) hlm 14.
[7] Abdurrahman Wahid, Melawan Melalui Lelucon, (Jakarta, Tempo, 2000) hlm 95.
[8] Ibid hlm 95-96.
[9] Jangan menilai buku dari sampulnya jiwa lebih dalam daripada kulit.
[10] Muhammad Nurul Ibad, Dhawuh Gus Miek, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2007) hlm 80.


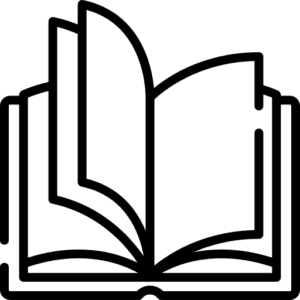

Bagus.. good job 👍
Serat Jaka Lodhang.. di tunggu jadi kesatuan ya.. alias di cetak jadi sebuah buku yang epic🤲📚
Soalnya lebih enak baca lewat buku.. bagi saya.. dengan gambar” di dalamnya yang bagus.. seperti di atas☝️