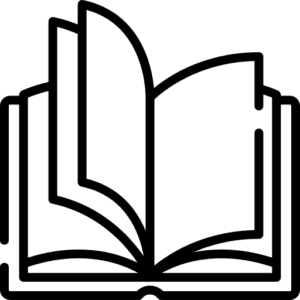Dalam kearifan Jawa, nama Semar tidak hanya menempati ruang naratif dalam jagad pewayangan, menjadi pamomong para kesatria, atau pemimpin Punakawan. Lebih dari itu, sosok Semar telah menjelma sebagai eksistensial yang hidup di tengah masyarakat. Figur sentral dalam kosmologi sekaligus perlambang kearifan lokal. Semar merupakan Dahyang, manifestasi (tajalli) kekuatan ilahi dalam rupa rakyat jelata. Bijak, namun bersahaja. Sakti tapi tak jumawa. Dalam Atlas Walisongo, Agus Sunyoto menyatakan, Semar merupakan nabi bagi penduduk Tanah Jawa era purba. Dia membawa ajaran yang dikenal dengan nama Kapitayan.
Namun dalam perkembangannya, figur Semar muncul dalam bentuk lain, khususnya dalam praktik ritual di tengah masyarakat. Menjadi figur sentral dalam mantra-mantra pengasihan. Figur yang bijaksana tersebut diseru dalam mantra untuk menundukkan orang lain. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, Apakah penggunaan nama Semar dalam konteks mantra pengasihan menunjukkan penurunan sakralitas? Ataukah sekadar dinamika budaya?
Semar dan transformasi budaya
Budaya bukanlah artefak, tapi organisme yang hidup dan lentur. Dalam perjalanannya, budaya selalu bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi zaman yang dihadapi. Kebudayaan juga tak mengenal dikotomi―antara sakral dan profan, gaib dan nyata, lucu dan luhur. Semua merupakan satu kesatuan (unity). Dalam konteks ini, figur Semar bisa dimana saja. Ia bisa menjadi penghibur dalam pertunjukan wayang sekaligus representasi mantra dari seorang pecinta.
Mantra dengan idiom Semar tidak hadir dalam ruang kosong. Lahir dari kebutuhan manusia akan cinta, pengakuan, dan rasa ingin memiliki. Muncul dari kondisi yang kering kasih sayang, namun ingin memegang kendali. Dan Semar-pun dipanggil, bukan untuk membimbing, tapi membujuk, atau barangkali memaksa seseorang untuk jatuh cinta. Maka, Semar menjadi figur yang terbelah. Di satu sisi ia adalah pamomong Pandawa―penjaga kebenaran. Tapi di sisi lain―menjadi mantera, alat, instrumen―untuk memanggil cinta yang tak kunjung datang. Dalam konteks ini, Semar merupakan medium energi―menjadi nama bagi kekuatan pengasihan, karena ia simbol dari welas asih itu sendiri.
Maka, penggunan nama Semar dalam mantra―bukan bentuk profanisasi, degradasi, atau banalitas budaya, tetapi lebih kepada perluasan makna. Mantra-mantra ini adalah ekspresi spiritual rakyat kecil yang tak terjangkau oleh teologi sistematik, tetapi justru sangat dekat dengan pengalaman batin sehari-hari. Ia juga menunjukkan, bahwa simbol-simbol klasik masih tetap relevan, selalu menemukan bentuk barunya. Bahkan dalam urusan asmara, simbol Semar tetap membawa welas asih, ketulusan, dan membimbing.
Meski tidak ada dikotomi budaya, paradigma Jawa acapkali berangkat dari keyakinan mistik. Bahwa kata-kata dipercaya sebagai energi. Ada adagium yang berbunyi, “Asmo kinaryo japa” bahwa kata-kata adalah doa yang bertuah. Karenanya, kata-kata bukan representasi makna, tetapi kekuatan itu sendiri. Maka idealnya, sebuah mantra harus disertai dengan ritus, dengan tirakat, dengan batin yang menyatu dengan tujuan.
Semar, Mantra, dan Cinta
Terdapat tiga mantra pengasihan yang populer―menggunakan figur Semar sebagai kata kunci. Semar Mesem, Semar Nangis, dan Semar Kuning. Mantra-mantra tersebut merupakan pertemuan Islam dengan budaya lokal, yang arkais dengan sufistik. Sebuah akulturasi khas dari bumi Nusantara.
Mari perhatikan bagaimana bunyi mantra Semar Mesem :
Srikandhi abang iya lakinira si Arjuna, adegku Togog, lungguhku Semar, sira welas sira asih ndulu badan saliraku si…
Srikandhi yang berkulit merah kekasihmu adalah Arjuna, Aku berdiri tak ubahnya Togog, dudukku seperti Semar, kamu welas asih ketika melihat sekujur badanku. Si…
Dalam mantra ini, tokoh Srikandhi dan Arjuna dipanggil. Bukan untuk menghidupkan narasi Mahabarata. Bukan. Melainkan menciptakan atmosfir asmara yang mempunyai landasan mitologis. Ada kerinduan untuk dipandang dengan penuh belas kasih, bukan oleh Tuhan semata, tapi juga manusia. Si pengucap menganalogikan berdirinya seperti Togog, duduk seperti Semar, menyiratkan keinginan memiliki ketenangan, aura suci, atau kebijaksanaan seperti kedua pamomong tersebut.
Ada pula mantra Semar Nangis, yang cukup menggetarkan hati karena diucapkan dengan suara yang lirih;
Bismillahirrahmanirrahim condhong lunga anggendhong Semar kari anangis ya aku anake Randha Kasihan, teka welas teka asih si… menyang sariraku. Sir teka, sir teka, sir teka sirullah sir ana ing awakku, ana pangucapku welasa sejaku welas asih karep aku, Kinasihana dening Allah lailahaillallah Muhammadarasulullah.
Bismillahirrahmanirahim. Cenderung pergi dengan menggendong Semar tinggallah menangis. Aku ini putra janda terkasih, datang dengan belas kasih, si… datang kepadaku. Berniat datang, berniat datang, berniat datang rahasianya Allah yang berada di badanku, di ucapanku, berbelas kasihanlah akan niatku, belas kasih terhadap keinginanku, dikasihi oleh Allah lailahaillallah Muhammadarasulullah.
Terasa ada aura sedih yang merembes dalam narasi Semar Nangis. “Tinggallah menangis. Aku ini putra janda terkasih”. Kata “janda” memikul beban kultural tertentu. Sebuah identitas yang acapkali disingkirkan―diremehkan, namun justru sebagai sumber kekuatan. Seperti anak yang merindukan pelukan ibu, maka menangis dalam konteks mantra ini bukanlah kelemahan, tapi pemanggil kekuatan batin. Air mata menjadi bahasa rahasia menuju Ilahi. Semar dalam wujudnya yang menangis, menjadi representasi dari penderitaan manusia yang tetap ingin mencintai, diterima, meski dengan luka.
Sedangkan mantra Semar Kuning lebih terkesan surealis;
Bismillahirrahmanirrahim, Ajiku Semar Kuning, sungsum wuyung semelang, tetese angin nangis-nangisi….maring badan saliraku, teka kedhep teka lerep, asih saking kersane Allah, lailahaillallah Muhammadarasulullah Salallahualaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim, Mantraku Semar Kuning, di dalam tulang sungsum tersembunyi gejolak asmara yang disertai rasa khawatir, tetesan angin seperti tangisan, menangisi… terhadap sekujur badanku, datang dengan takluk, khawatir lailahaillallah Muhammadrasulullah Salallahualaihi wasallam.
Mantra Semar Kuning menyimpan hal-hal yang paradoks. Membuat kita tertawa sekaligus merasa asing. Disatu sisi ada rasa cinta, namun di sisi lain muncul rasa khawatir. Mantra ini juga menegasikan bahwa dalam cinta, tunduk, dan belas kasih bukan kelemahan, tetapi kekuatan. Kekuatan yang justru datang dari kehendak Tuhan.
Alhasil, Semar bukanlah tokoh statis. Ia hadir, tersenyum, kadang juga menangis. Ia bergerak bersama kesadaran kolektif masyarakat Jawa. Kehadirannya dalam mantra-mantra cinta menunjukkan kebutuhan batin terhadap kasih sayang akan terus hidup dalam ruang budaya. Bahkan dalam bentuk yang tampak mistik dan sederhana, tetapi memiliki dimensi spirit yang tak bisa dikesampingkan. Wallahu a’lam.
Bahan Bacaan
Wiryapanitra, tt, Wejangan Walisanga, Solo: Sadu Budi.
Sang Indrajati, tt, Primbon Sabda Sasmaya, Solo: Sadu Budi.
Agus Sunyoto, 2013, Atlas Walisongo, Bandung: Imania.
Dr. Suwardi EndraswaRa, 2013, Teori Kritik Sastra, Yogyakarta: CAPS.