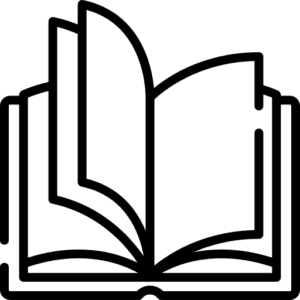Meski telah wafat 14 tahun silam, tepatnya 6 Agustus 2009, penyair besar Indonesia WS Rendra, telah menyisakan sejuta inspirasi bagi para penikmat puisi-puisinya. Mungkin saya adalah salah satu diantara mereka. Kini, kata-kata Rendra telah bertransformasi menjadi pepatah abadi. Pepatah yang menggugah jiwa-jiwa lelah dan penat akan problematika kehidupan.
Penyair bergelar ‘burung merak’ itu telah meninggalkan sejumlah puisi bertema kritik sosial. Puisi-puisi tersebut terkumpul dalam buku, ‘Potret Pembangunan Dalam Puisi’. Sebelumnya, buku ini telah terbit di Leiden dengan judul ‘Pamfleten Van een Dichter’. Sasaran kritik Rendra sangat beragam, mulai dari aspek pendidikan, politik, ekonomi, seni, maupun kebudayaan. Rendra kerap menyuarakan aspirasi kaum marginal, jeritan petani miskin, warga yang rumahnya tergusur, hingga para pelacur yang menjadi sasaran kebencian namun tetap dinikmati kemolekan tubuhnya. Bagi WS Rendra, tugas penyair tidak hanya menggambarkan keindahan alam dengan kata-kata yang memikat pendengarnya. Menyihir kesadaran. Atau pengundang dercak kagum. Tidak. Penyair harus mempunyai fungsi dan peran sosial tersendiri. Ia memberikan terminologi ‘penyair salon’ untuk kategori penyair yang hanya memuja keindahan belaka. Dus, karena kritik Rendra tersebut, penyair bernama lengkap Willibrordus Surendra Broto Rendra sempat mengalami pencekalan pada masa rezim Orba.
Diantara sekian kritik sosial Rendra yang masih relevan, adalah kritiknya terhadap pendidikan Indonesia. Melalui ‘sajak seonggok jagung’, Rendra telah menggambarkan realitas pendidikan di Indonesia yang timpang.
“Seonggok jagung di kamar
dan seorang pemuda
yang kurang sekolahan.
Memandang jagung itu,
sang pemuda melihat ladang;
ia melihat petani;
ia melihat panen;
dan suatu hari subuh,
para wanita dengan gendongan
pergi ke pasar
Dan ia juga melihat
suatu pagi hari
di dekat sumur
gadis-gadis bercanda
sambil menumbuk jagung
menjadi maisena.
Sedang di dalam dapur
tungku-tungku menyala.
Di dalam udara murni
tercium kuwe jagung
Seonggok jagung di kamar
dan seorang pemuda.
Ia siap menggarap jagung
Ia melihat kemungkinan
otak dan tangan
siap bekerja
Tetapi ini :
Seonggok jagung di kamar
dan seorang pemuda tamat SMA
Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa.
Hanya ada seonggok jagung di kamarnya.
Ia memandang jagung itu
dan ia melihat dirinya terlunta-lunta.
Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik.
Ia melihat sepasang sepatu kenes di balik etalase.
Ia melihat saingannya naik sepeda motor.
Ia melihat nomor-nomor lotre.
Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal.
Seonggok jagung di kamar
tidak menyangkut pada akal,
tidak akan menolongnya.
Seonggok jagung di kamar
tak akan menolong seorang pemuda
yang pandangan hidupnya berasal dari buku,
dan tidak dari kehidupan.
Yang tidak terlatih dalam metode,
dan hanya penuh hafalan kesimpulan,
yang hanya terlatih sebagai pemakai,
tetapi kurang latihan bebas berkarya.
Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan”
Dalam mengawali narasinya, Rendra menggambarkan dua anak muda yang amat kontras perbedaannya. Bumi versus langit. Baik latarbelakang, kondisi sosial, hatta cara pandangnya terhadap realitas kehidupan. Bila mengacu Taksonomi Bloom, disatu pihak terdapat pemuda yang lebih dominan dalam aspek psikomotorik dan afektif, namun lemah dalam aspek kognitif. Pemuda dengan cara pandang praktis terhadap dunia berikut solusi dan cara mengatasi problematikanya. Ia terlatih dalam skill dan pengalaman, walaupun dalam skala teori pengetahuan begitu lemah. Namun, saat dihadapkan terhadap kenyataan, tipe demikian yang notabene lebih siap untuk menghadapi tantangan dengan seutas senyuman positif.
Di lain pihak, anak muda yang dididik dalam berbagai macam teori. Mengandalkan kecerdasan intelektual belaka. Namun taraf skill dan kemampuan motorik sangat lemah. Lebih dominan dalam aspek kognitif, mempunyai nilai cukup tinggi dalam berbagai mata pelajaran, serta hafal berbagai jenis teori ilmiah. Kendati demikian, ketika dihadapkan dengan kenyataan yang menerpa, ia lemah. Rungkat. Tidak bisa mengantisipasi dengan baik. Tidak tahu harus berbuat apa.Teori yang dikuasainya, hanya menggumpal didalam otak. Menjadi angan-angan kosong yang menakut-nakuti hati sanubari. Lantas ia keluarkan melalui lisan-lisan kotor penuh kritik, hujatan, keluh-kesah, dan caci maki.
Aktor kenamaan Indonesia, Slamet Rahardjo, dalam mengapresiasi puisi WS Rendra tersebut, membuat dua kategori.
Kategori pertama ia beri term ‘terdidik’ dan kedua dengan term ‘berijazah’. Kedua-duanya adalah simbiosis mutualisme, saling menunjang satu sama lain. Berijazah tanpa ‘terdidik’, berakibat seperti dalam lagu ‘Sarjana Muda’ karya Iwan Fals, ‘Sarjana Muda bingung mencari kerja mengandalkan ijazahmu’. Sungguh sangat ironis sekali realitas di negeri ini.
Selebihnya, WS Rendra mengungkapkan kegelisahannya akan dampak pendidikan yang hanya menekankan salah satu aspek yang sangat dominan terhadap generasi muda.
“Aku bertanya :
Apakah gunanya pendidikan
bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing
di tengah kenyataan persoalannya?
Apakah gunanya pendidikan
bila hanya mendorong seseorang
menjadi layang-layang di ibukota
kikuk pulang ke daerahnya?
Apakah gunanya seseorang
belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran,
atau apa saja,
bila pada akhirnya,
ketika ia pulang ke daerahnya, lalu berkata :
“Di sini aku merasa asing dan sepi!”
Berangkat dari puisi ini, WS Rendra mengharapkan perbaikan sistem dan mutu pendidikan Indonesia yang lebih baik dimasa-masa mendatang. Sebuah institusi pendidikan yang tidak hanya mengandalkan salah satu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun ketiganya harus bersinergi dalam satu-kesatuan, tegak linear, satu rangkaian, dan tidak berdiri sendiri. Dalam istilah yang digunakan Ary Ginanjar Agustian, antara intelektual quotient, emosional quotient, dan spiritual quotient harus terserap semua. Alhasil dengan demikian, akan terealisasi dengan baik visi misi pendidikan Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 45, ‘Mencerdaskan kehidupan bangsa’. Wallahu a’lam bish Shawab.