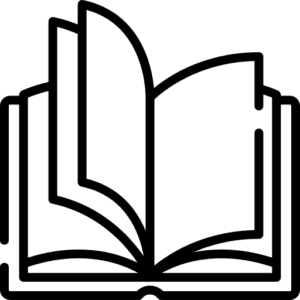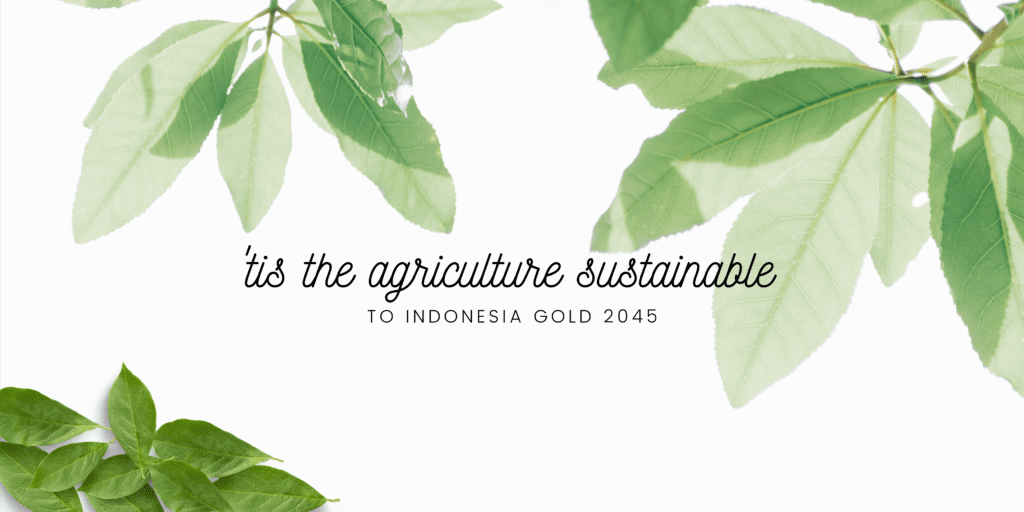
Karakteristik bahan baku dan proses pengomposan sangat menentukan kualitas pupuk kompos yang dihasilkan. Kondisi suhu, pH, rasio karbon/ nitrogen (C/N), dan kelembapan juga berpengaruh dalam proses pengomposan sehingga harus dioptimasi. Proses pengomposan dapat dilakukan salah satunya menggunakan metode vermi-composting. Pada metode vermi-composting dekomposisi terjadi karena adanya kerjasama antara cacing dan mikroorganisme. Cacing akan memakan dan memproses bahan organik dalam sistem pencernaannya kemudian mengekskresikan kotoran yang kaya akan nutrisi organik. Sedangkan mikroorganisme dapat menghasilkan enzim yang dapat mendegradasi substrat organik menjadi molekul yang sederhana.
Produk yang dihasilkan dari kerja cacing dan mikroorganisme inilah yang nantinya dapat dimanfaatkan tanaman untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Jerami padi, pupuk kandang, dan batang pisang yang diparut disusun dalam bentuk windrow atau gundukan-gundukan memanjang. Selama penyusunan windrow, dilakukan penambahan air agar kadar air mencapai 60% yang merupakan kondisi yang sesuai untuk pengomposan. Proses pengomposan selanjutnya dilakukan secara anaerobik selama sekitar 40 hari dengan cara ditutup dengan plastik dan aerobik dengan cara membuka tutup plastik selama sekitar 40-50 hari.
Cacing jenis ANC atau African Night Crawler yang memiliki ukuran dua kali lebih besar dari cacing tanah biasa sangat populer digunakan dalam vermi-composting karena dapat memakan lebih banyak sampah. Cacing ini ditambahkan pada saat proses pengomposan aerobik. Proses penyiraman windros dilakukan secara berkala dan dalam takaran tertentu karena air sangatlah penting untuk perkembangan dan pertumbuhan cacing serta berpengaruh terhadap efisiensi produksi vermicast (produk vermi-composting) oleh cacing. Dari proses pengomposan, dihasilkan vermicast sebesar 50% dari total bahan baku awal (1Nghi dkk., 2020). Vermicast dapat menyediakan makronutrien dan mikronutrien tersedia yang dibutuhkan oleh tanaman. Hasil studi menunjukkan bahwa vermicast mengandung karbon organik yang berkisar antara 9,8-13,4%, nitrogen 0,51-1,61%, fosfor 0,19-1,02%, kalium 0,15-0,73%, kalsium 1,18-7,61%, magnesium 0,093-0,568%, natrium 0,058-0,158%, seng 0,0042-0,110%, tembaga 0,0026-0,0048%, besi 0,2050-1,3313%, dan mangan 0,0105-0,2038% (Adhikary, 2012).
Pemanfaatan jerami sebagai kompos dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan limbah pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan petani akan pupuk kimia. Sebagian dari limbah jerami padi saat ini telah dimanfaatkan sebagai pakan hewan ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap hijauan makanan ternak (HMT) karena perubahan musim. Ketersediaan hijauan di musim kemarau cenderung rendah padahal pakan harus tetap tersedia. Pemanfaatan jerami sebagai pakan ternak secara langsung memiliki tingkat kecernaan yang masih rendah karena kandungan serat kasar yang tinggi yaitu 32-40% dan kandungan protein kasarnya cukup rendah sebesar 3-4% (Hardiana dkk., 2022). Jerami padi mengandung selulosa dan hemiselulosa yang terbungkus lignin sehingga sulit didegradasi oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh mikroba dalam saluran pencernaan ruminansia. Selain itu jerami padi juga mengandung silikat dalam jumlah yang cukup tinggi sehingga mikroba dalam rumen hewan ternak sulit untuk mencernanya. Permasalahan tersebut dapat diatasi menggunakan pendekatan bioteknologi yaitu teknik fermentasi.
Silase adalah makanan ternak yang terbentuk dari fermentasi anaerobik (tanpa adanya oksigen) rumput, pakan hijauan lainnya, atau bisa juga dengan memanfaatkan jerami padi yang memiliki kadar air cukup. Pakan ini dapat disimpan sehingga dapat mengatasi kekurangan pakan pada saat musim kemarau. Fermentasi oleh bakteri asam laktat terjadi dalam kantong plastik kedap udara (silo) atau drum sehingga terhindar dari oksigen dan mikroorganisme aerobik yang berasal dari luar silo. Pada proses fermentasi silase, penambahan bahan aditif biasanya dilakukan untuk meningkatkan kandungan nutrisi, mempercepat proses fermentasi, dan meningkatkan performa hewan ternak sehingga lebih ekonomis.
Bersampung ke part 3