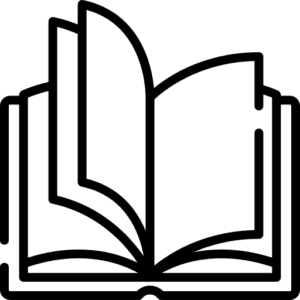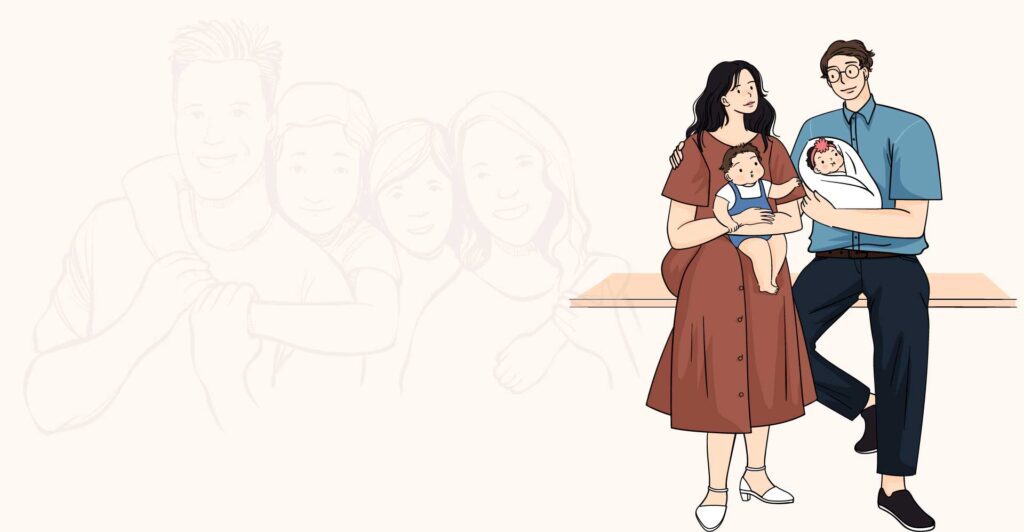
Pada pendekatan romantisisme, sastra berhenti menjadi semata-mata fiksi yang cenderung untuk memperindah situasi kehidupan secara romantis. Bentuk dan muatannya dipenuhi dengan obsesi–personal. Atau bisa dikatakan semata hanya tentang perjuangan batinnya yang egoistis dan kesabaran terhadap penderitaan dengan hampir tanpa memperhatian aspek-aspek di luar dirinya sendiri.
Sedangkan pendekatan para realis, jarang sekali berbicara sebagai orang pertama; sastranya merupakan deskripsi yang jujur mengenai kehidupan yang dialami oleh individu konkret dalam cara-cara yang unik. Menjadikan sastra memiliki peran (engagee, kata Sartre) untuk membantu manusia dalam menyelesaikan problemnya.
Kedua pendekatan tersebut menjadi sangat penting sebagai penopang tujuan (tradisional) sastra; kebenaran.
Seiring perkembangan jaman, muncul kebaruan-kebaruan sebagai pengembangan pendekatannya. Sayang, kebaruan/ perkembangan cabang pendekatan ini mulai diklasifikasikan dalam kotak-kotaknya sendiri, dan kemudian dipahami secara sempit perkotak saja. Sedangkan pemahaman tradisional yang luas dan utuh tentang tujuan sastra; kebenaran, malah terkikis dalam pembelajaran cabang-cabangnya. Sehingga, sastra mulai kehilangan esensinya; keindahan.
Karya sastra dibatasi kewenangannya hanya sekedar menjadi alat; untuk kesenangan pribadi belaka, dibaca-baca dan dikagumi sendiri oleh penulisnya. Pun menjadi alat perjuangan sebagaimana yang diangankan orang sejak ”roman bertendens” di masa lampau hingga ”sastra islami” yang muncul pada tahun-tahun belakangan.
Sastra tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang luas secara cakupan. Hanya berupa idiom, sempit, dan kemudian memiliki kewajiban untuk dipahami sebagai kebenaran berdasar satu perspektif saja (lurus). Jalan lurus mencapai pemaknaan inilah yang pada akhirnya menihilkan karya-karya sastra sebagai sebuah jalan melingkar; di mana sisi estetis dan realisnya dimaknai secara terpisah.
Kebenaran yang sebelumnya adalah tujuan, kini semakin dikerdilkan sebagai sastra adalah kebenaran itu sendiri. Nah ini… susah kalau sudah kayak gini. Para pemuja moralitas akan semakin kesetanan (baca; skeptis), karena pondasi dasarnya; kebenaran adalah sastra itu sendiri. Budaya tutur yang direpresentasikan dalam teks sastra, malah jadi berlebihan kalau nuturi. Jalannya lempeng bin lurus aja. “Jangan jadi orang jahat!” hanya itu. “Orang jahat, masuk neraka!” hanya itu. “Babi itu haram!” hanya itu. La kalau cuma mau nuturi gitu, yo ndak perlu pakai sastra-sastraan. Dan memang hal ini tidak penting, karena semua orang sudah tau.
Yang kita perlukan adalah jalan melingkar dan ketersesatan yang menjadi pembelajaran secara kontemplatif. Tidak hanya berbicara “jangan jadi orang jahat!”, lebih dari itu, harus ada pemahaman tentang jahat yang bagaimana? bisa jadi, di ruang fiksi, orang yang tidak mencopet di tengah lingkungan copet, adalah orang jahat bagi para pencopet. Perlu ada pemahaman-pemahan yang kompleks, dan pemaknaan yang berlapis, agar capaian kebenaran benar-benar baik dan benar.
“Orang bisa mendapatkan kesadaran baru dengan membaca sastra, tetapi prosesnya tidak akan seperti orang terbangun mendadak dari tidur lelap oleh bunyi kentongan dan beduk sahur.”
Kurang lebih seperti itu. Sehingga, kesadaran-kesadaran yang terbangun adalah kesadaran pemahaman kebenaran yang bersifat kontemplatif. Bukan berupa pengalaman hafalan doktrin, atau sekedar ‘plang’ peringatan ‘dilarang kencing di sini, kecuali anjing!’. Semua orang sudah tau!
Malang, –